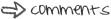SAINS dan sastra adalah dua entitas yang luar biasa luas, yang beririsan
setidaknya di dua ranah penting. Pertama adalah ranah ”metafisis”:
sains dan sastra sama berupaya mengajukan model tentang kenyataan. Yang
kedua adalah ranah formal: sains dan sastra sama bermain dengan
manipulasi simbolik.
Model kenyataan yang diajukan sains tampak
paling jelas pada kosmologi, mekanika kuatum dan biologi-evolusioner;
manipulasi simbolik sains terlihat paling terang pada matematika murni.
Jika
bahan dasar sastra adalah bunyi serta aksara yang membentuk dan
menunjuk kata, bahan dasar matematika adalah angka atau notasi yang
mengacu bilangan dan operasi matematika. Dengan bahan dasar yang tumbuh
jadi beragam bentuk itu, matematika (sains formal) jadi bahasa
transparan yang memungkinkan munculnya makna tunggal dan stabil; bahasa
yang mampu merepresentasikan pikiran dan kenyataan empirik secara tegar.
Sebagai
bahasa tingkat kedua, matematika telah dimurnikan dari sifat acak
bahasa yang mutlak dan meraja sebelum adanya figurasi dan makna.
Dalam
matematika, tanda bahasa boleh berubah dan beraneka, tetapi artinya
sudah tertetap dan tertentu. Dalam puisi, meski tetanda telah tertetap
dan tertentu, ada banyak makna yang mungkin rekah.
Bagi mereka
yang memuja puisi karena kekuatan ajaibnya memperkaya bahasa, matematika
memang bisa tampak bagai ”penjahat” yang akan membunuh bahasa dengan
menyedot darah ambiguitas dan luapan makna darinya.
Dalam
khazanah sastra modern Indonesia, penyair seperti Soebagio Sastrowardoyo
dan Goenawan Mohamad pernah menuliskan pandangan miring terhadap
”pemiskinan makna” yang dilakukan oleh sains, yang tampak niscaya karena
watak dasar bahasa matematis.
Namun, jika dihadapi dengan
stimmung ala Nietzsche, bangunan matematis juga sanggup membuat orang
mendengar gagasan di belakang simbol matematis itu, intuisi di belakang
gagasan itu, dan Nalar di belakang intuisi itu.
Struktur deduktif
Selain
ketunggalan makna, bantuan terbesar matematika adalah penataan kepingan
pemikiran tentang alam fisis dengan kokoh, rapi dan anggun, dalam suatu
struktur deduktif yang mirip bangunan geometri Euclides.
Suatu
teori dapat dilihat sebagai suatu cabang matematik yang
aksioma-aksiomanya menyatakan hubungan kuantitatif antara berbagai
konsep fisik. Adapun strukturnya adalah serangkaian deduksi, dan
teoremanya adalah pembuktian matematis atas konsep-konsep tersebut.
Struktur
seperti ini, ditambah dengan pemberian bilangan kepada obyek dan
gejala, memungkinkan sebuah teori secara deduktif memberikan peristiwa,
dan menjabarkan konsekuensi dengan akurat.
Matematika murni
tingkat tinggi yang sekali waktu dianggap hal yang paling tidak praktis
dari segenap kegiatan manusia kian mengukuhkan diri sebagai alat tak
tergantikan dalam memahami kerja dan dimensi kolosal kenyataan semesta.
Kian banyak hal yang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk khayal apa pun yang
logis secara matematis akan mungkin juga terjadi secara fisis.
Ketika
sains belum berkembang menjadi sistem pengetahuan yang tertata secara
metodologis dan teruji secara empiris, sastra sungguh lebih dominan
dalam menyajikan model-model kenyataan yang kukuh.
Model
kenyataan (gambaran dunia, peta kognitif) mempunyai peran sangat penting
dalam kebudayaan. Dengan model itu, manusia menempatkan diri dalam
lautan ruang dan waktu yang luas tak terbatas. Dengan model itu pula
manusia menentukan hubungannya dengan manusia lain.
Yang menjadi
problem adalah: banyak model kenyataan yang masih dipegang teguh dan
terus direproduksi oleh sastra itu mungkin cocok di masa silam, tetapi
tak lagi memadai di masa kini.
Dua gerakan
Setidaknya ada
dua gerakan yang mencoba mengoreksi model kenyataan tua yang disebarkan
sastra. Pertama adalah gerakan posmodenis dekonstruksionis yang antara
lain menandaskan watak fiksi dalam sastra, khususnya sastra yang
dianggap sakral. Buat mereka, model kenyataan itu, meminjam Nietzsche,
adalah kesalahan yang tanpanya sejenis makhluk tak dapat hidup.
Gerakan
kedua datang dari sains (postmodernis konstruktif) yang berupaya
mengajukan gambaran dunia yang lebih lengkap dan teruji. Buat mereka,
kenyataan obyektif itu ada, dan lebih ajaib dari yang mungkin
dibayangkan.
Dalam pandangan dunia sains mutakhir, tak ada kuasa
terang dan kuasa gelap di alam semesta ini, tak ada kelompok manusia
yang secara esensial lebih istimewa dari yang lain, juga tak ada
kekuatan supernatural yang setiap saat bekerja tanpa henti mencampuri
urusan dunia. Sains mutakhir mendapati alam semesta ini bagai buku
kosong yang di dalamnya manusia harus menuliskan puisi.
Science
fiction kadang dianggap sebagai karya yang menautkan sains dan sastra.
Nyatanya, banyak bacaan fiksi ilmiah menghadirkan penyalahgunaan
khazanah sains secara menggelikan. Fiksi ini mungkin saja meminjam
temuan sains, spekulasi teoritisnya. Namun, semangat dan pandangan dunia
yang melatarinya adalah hal yang justru ditampik sains.
Edgar
Allan Poe (”Eureka”), Lewis Carrol (”Alice’s Adventure in Wonderland”),
Primo Levi (”The Periodic Table”), dan Jorge Luis Borges (”Ficciones”)
adalah sederet nama yang dengan kreatif berhasil memautkan sastra dan
sains.
Semua pencapaian utama dari para sastrawan di atas agaknya
bermula dari pengetahuan yang kukuh atas horizon terjauh sains (juga
sastra) di zaman mereka.
Pemahaman atas batas-batas itu
membimbing mereka mendorong lebih jauh tepian terluar itu sambil membuka
cakrawala kemungkinan baru yang lebih menakjubkan.
 Kita tentu pernah mengetahui
banyak sekali cerpen dan novel yang tersedia di toko buku. Seringkali
kita juga membaca kedua jenis karya sastra tersebut, namun banyak juga
yang belum mengetahui apa perbedaan cerpen dan novel tersebut. Kita
dapat mengetahui perbedaan keduanya dari ciri – ciri kedua jenis karya
sastra tersebut. Banyak sekali perbedaan yang dapat diungkapkan ketika
kita membandingkan kedua jenis karya sastra tersebut.
Kita tentu pernah mengetahui
banyak sekali cerpen dan novel yang tersedia di toko buku. Seringkali
kita juga membaca kedua jenis karya sastra tersebut, namun banyak juga
yang belum mengetahui apa perbedaan cerpen dan novel tersebut. Kita
dapat mengetahui perbedaan keduanya dari ciri – ciri kedua jenis karya
sastra tersebut. Banyak sekali perbedaan yang dapat diungkapkan ketika
kita membandingkan kedua jenis karya sastra tersebut.